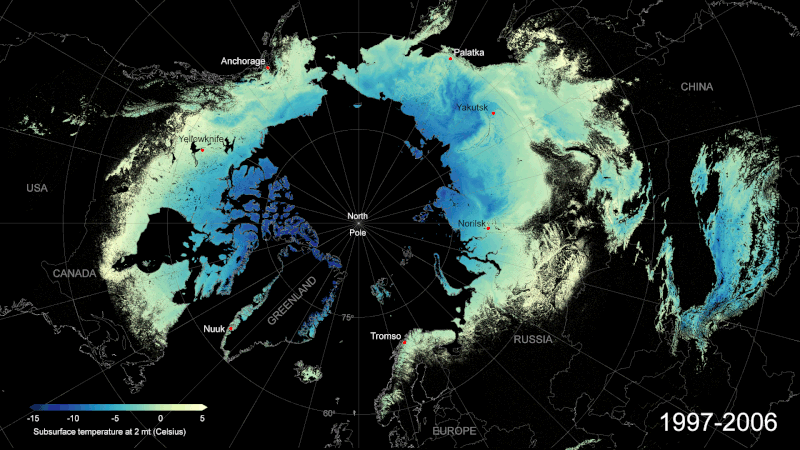Lebih dari 30.000 orang diperkirakan akan tiba minggu depan di ujung selatan Semenanjung Sinai Mesir – pejabat pemerintah, industrialis, ilmuwan, dan aktivis – semuanya bersatu dalam satu bisnis serius untuk mengatasi perubahan iklim . Frustrasi besar menjelang konferensi dunia terakhir tentang masalah ini, ke-27 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1995. Greta Thunberg telah memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak tidak berencana untuk hadir sampai tekanan publik mengubah rencananya.
Salah satu alasan suasana hati yang buruk adalah bahwa bencana cuaca tampak lebih sering dan intens sementara kemajuan menuju target emisi karbon tetap lambat. Negara-negara kaya juga gagal memenuhi janji mereka untuk membayar negara-negara miskin atas “kerugian dan kerusakan” yang disebabkan oleh dampak iklim dari industrialisasi mereka sebelumnya.
Perasaan marah dan takut mendominasi konferensi iklim tahunan. KTT ini “memiliki budaya zero-sum, penyanderaan, tawar-menawar, permainan tawar-menawar,” Alden Meyer, analis politik di E3G, sebuah think tank perubahan iklim yang berbasis di London, mengatakan kepada The New York Times.
Namun di luar arena politik yang kontroversial, keragaman pemikir dalam sains, filsafat, dan agama menunjukkan pengakuan terhadap kerangka kerja mental yang berbeda—mereka yang melihat atmosfer yang memanas bukan sebagai masalah untuk tindakan moral daripada sebagai panggilan untuk atmosfer mental yang baru.
“Memecahkan masalah perubahan iklim tidak akan berhasil jika kita membiarkan ketakutan kita mengalahkan kita,” Tyler Giannini, co-direktur Klinik Hak Asasi Manusia Internasional di Harvard Law School, mengatakan kepada The Harvard Gazette pada bulan April. “Memecahkan masalah akan membutuhkan kekuatan, komitmen, dan kreativitas komunitas global kita.”
Sebagian besar kreativitas ini melibatkan upaya, yang didorong oleh perubahan iklim, untuk mendamaikan sains dan agama. Diskusi-diskusi ini muncul dari berbagai tempat, dari Harvard’s Divinity School hingga The Nature Conservancy. Di Indonesia, program yang diluncurkan awal tahun ini oleh Pusat Studi Islam Universitas Nasional memperkenalkan kurikulum perubahan iklim ke 50 pesantren. Program ini dirancang untuk menanamkan pada siswa pendekatan pengelolaan lingkungan yang berakar pada nilai-nilai Islam.
Langkah-langkah seperti ini mencerminkan niat untuk memanfaatkan keragaman nilai-nilai agama untuk membantu dunia mengatasi dampak perubahan iklim. Namun mereka mungkin mengetuk pintu sesuatu yang lebih dalam – sebuah pendekatan yang oleh mendiang pemikir Prancis Bruno Latour digambarkan sebagai “rezim iklim baru”, sebuah tantangan yang sangat sulit sehingga ia menyerukan cara berpikir baru tentang perubahan iklim.
Perspektif ini akan bekerja pada 13 November pada konferensi iklim dua minggu di Mesir. Perwakilan dari agama-agama besar dunia akan berkumpul di Gunung Sinai, tempat Musa menerima Sepuluh Perintah Allah, untuk bersama-sama menegaskan kegunaan hukum spiritual bagi respons global terhadap perubahan iklim. Pertemuan mereka bukanlah permintaan pasif untuk campur tangan ilahi. Ini, seperti yang dikatakan oleh berbagai penyelenggara, adalah “panggilan untuk memeriksa kembali sikap yang mendalam dan mengidentifikasi cara untuk mengubah sikap itu demi kesejahteraan Bumi”.

“Sarjana musik ekstrem. Penggemar kopi yang ramah. Penginjil makanan. Pembaca hardcore. Introvert freelance. Pengacara Twitter.”