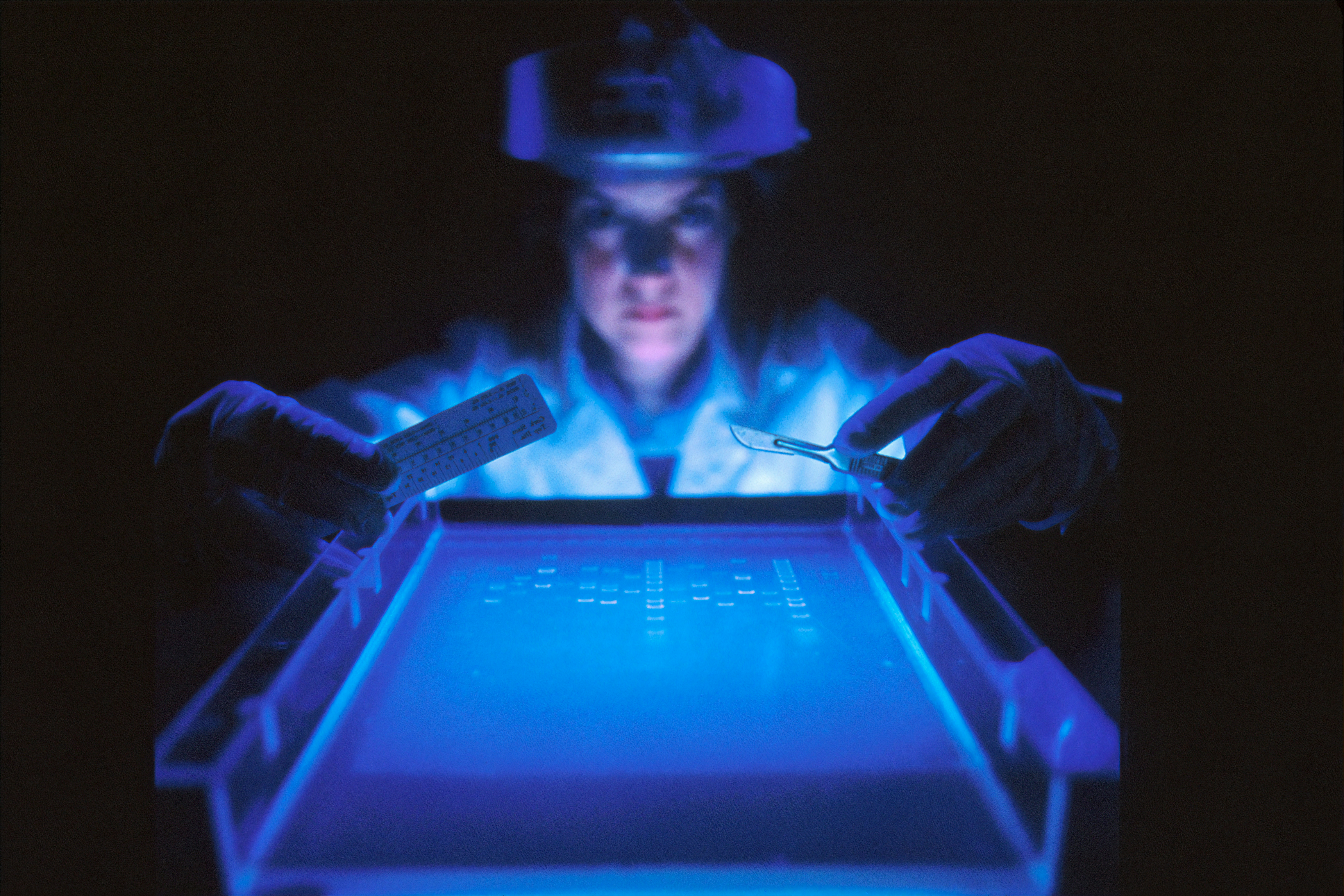PADA 2015 Asit Biwas, seorang profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, dan Julian Kirchherr, seorang peneliti di University of Oxford, menulis sebuah opini yang sangat menarik dan penting di Waktu selat berjudul “Guru, Tidak Ada yang Membacamu”.
Artikel tersebut memberikan perspektif baru tentang bagaimana seharusnya akademisi berpikir tentang diri mereka sendiri dan peran mereka dalam masyarakat yang terus berubah. Dalam artikel tersebut, mereka berpendapat bahwa banyak ide cemerlang dari akademisi tidak berdampak signifikan pada debat publik dan pembuatan kebijakan.
Hal ini dikarenakan para akademisi hanya membagikan pemikiran mereka dalam jurnal akademik yang hanya dibaca oleh rekan-rekan akademik mereka. Keduanya bahkan menunjukkan bahwa rata-rata artikel dalam jurnal ilmiah hanya dibaca oleh sekitar sepuluh orang, yang tidak banyak mengubah masyarakat. Oleh karena itu, agar lebih berdampak, akademisi harus menulis lebih banyak opini untuk dibaca oleh pengambil keputusan dan publik sehingga dapat mempengaruhi wacana publik atau bahkan pengambil keputusan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar tentang sejauh mana karya para akademisi, khususnya ilmu-ilmu sosial di Indonesia, relevan dengan masalah dunia nyata saat ini.
Setidaknya ada tiga cara agar akademisi dan akademisi, khususnya ilmu sosial, lebih relevan untuk menjawab tantangan Indonesia.
Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Harold Koh, seorang profesor di Yale Law School dan mantan penasihat hukum Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, penting bagi seorang akademisi untuk juga memiliki pengalaman praktis aktual sebagai pembuat keputusan senior di pemerintahan. Dengan demikian, mereka memiliki gagasan tentang topik yang mungkin penting dan relevan bagi siswa yang akan dipraktikkan nanti.
Dia bahkan mencontohkan berapa banyak akademisi di Amerika Serikat yang menjadi pejabat senior pemerintah. Ini tidak hanya membentuk pengembangan kebijakan yang dibenarkan secara akademis, tetapi juga teori di dunia akademis.
Memang, banyak menteri dan pejabat senior pemerintah Amerika Serikat memiliki pendidikan universitas. Joseph Nye, Ann Marie Slaughter, Janet Yellen dan Henry Kissinger hanyalah beberapa di antaranya. Mereka telah menjabat sebagai pejabat senior pemerintah dengan kredensial akademis yang kuat.
Setelah menduduki jabatan pemerintahan, mereka kembali mengajar dan mengembangkan karya akademisnya berdasarkan pengalaman sebagai pejabat pemerintah. Pengalaman-pengalaman ini kemudian membentuk karya akademis mereka, yang relevan dengan masalah dunia nyata dan tidak hanya berdasarkan teori yang sulit diterapkan.
Sejak Orde Baru di bawah Suharto (1967-1998), Indonesia memiliki tradisi yang kuat dari akademisi dan profesor yang menjabat sebagai menteri dan pejabat senior.
Dengan demokrasi yang lebih sedikit dan hampir tidak ada koalisi partai, Suharto memiliki kebebasan untuk memilih menteri. Akibatnya, para teknokrat dan akademisi dengan gelar di bidang tersebut telah diberikan posisi sebagai pengambil keputusan utama.
Hari ini, berkat demokratisasi, lebih banyak partai politik dan koalisi telah memaksa presiden untuk menyambut politisi sebagai menteri dan pejabat senior, kadang-kadang bahkan dengan latar belakang profesional dan keahlian yang minimal.
Akibatnya, lebih sedikit profesional di bidang khusus, termasuk akademisi, yang duduk sebagai menteri pemerintah.
Kedua, seperti yang Biwas dan Kirchherr nyatakan dalam editorial mereka, lebih banyak ilmuwan sosial Indonesia harus berbagi ide-ide mereka di luar rekan-rekan akademis mereka di jurnal akademik. Mereka juga harus menargetkan audiens yang lebih besar dan mempublikasikan penelitian mereka di media yang lebih populer, yang akan dibaca oleh masyarakat umum dan pembuat kebijakan.
Saat ini semakin banyak outlet online untuk berbagi pengetahuan dengan khalayak yang lebih luas. Dengan berbagi ide dengan masyarakat umum, mereka akan memenuhi kewajiban mereka untuk mencerdaskan bangsa.
Ketiga, civitas akademika Indonesia harus lebih menghargai studi interdisipliner, yang penting untuk menangani isu-isu global saat ini.
Di dunia yang dinamis ini, sebagian besar masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu disiplin akademik. Banyak masalah dan tantangan yang paling baik diselesaikan melalui kolaborasi dan perspektif interdisipliner.
Misalnya, pandemi adalah masalah yang melibatkan para ahli di bidang kesehatan, kebijakan publik, ekonomi, sosial, hukum, dan banyak disiplin ilmu lainnya. Masalah lain seperti keamanan siber, teknologi, kesehatan global, dan gender adalah masalah yang membutuhkan lebih dari satu disiplin untuk ditangani.
Oleh karena itu, Anda memerlukan seseorang yang mengetahui pendekatan interdisipliner ini atau sekolah yang menyelenggarakan studi multidisiplin ini. Di banyak negara maju seperti Amerika Serikat, akademisi dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda cenderung lebih diapresiasi karena akan memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah tertentu.
Misalnya, seseorang dengan gelar sarjana hukum dan doktor di bidang kesehatan global akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi masalah kesehatan masyarakat. Atau seseorang dengan gelar sarjana hukum dan TI mungkin lebih memahami keamanan siber dan privasi. Misalkan Indonesia mempertahankan pandangan tradisionalnya tentang disiplin akademis linier ini. Akademisi Indonesia akan kurang kompetitif secara internasional dan akan lebih sulit bagi civitas akademika untuk menghadapi tantangan masa depan yang dihadapi negara.
Selain itu, Indonesia juga tertinggal dalam hal sekolah pascasarjana multidisiplin dengan penelitian yang lebih berorientasi pada kebijakan. Lagi-lagi banyak negara maju seperti AS, Inggris, bahkan Singapura memiliki sekolah pascasarjana yang memiliki sifat interdisipliner yang melimpah. Sebagian besar universitas di Indonesia masih memiliki sistem fakultas tradisional. Di dalam negeri, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial masih sangat terpisah dan jarang berbicara dan berkolaborasi satu sama lain.
Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka saat ini, yang mengizinkan mahasiswa mengambil mata kuliah dari berbagai sekolah atau jurusan, merupakan awal yang baik untuk menjembatani kesenjangan antara sistem pendidikan interdisipliner. Tapi tentu perjalanan masih panjang. Oleh karena itu, untuk mengatasi isu-isu global saat ini dan masa depan serta membuat akademisi lebih relevan, adalah penting bahwa sivitas akademika Indonesia, khususnya ilmu-ilmu sosial, membantu membentuk debat kebijakan publik dan pembuatan kebijakan politik di Indonesia. – The Jakarta Post / ANN

“Sarjana musik ekstrem. Penggemar kopi yang ramah. Penginjil makanan. Pembaca hardcore. Introvert freelance. Pengacara Twitter.”